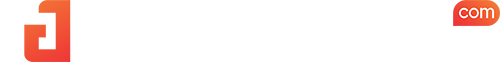AGAM (RA) - Di Salareh Aia Timur dan Salareh Aia Induk, hujan bukanlah sesuatu yang asing. Ia datang hampir setiap hari, turun perlahan dari dinding-dinding bukit yang mengelilingi desa.
Namun pada Kamis sore, 27 November 2025, hujan berubah menjadi ancaman. Awan gelap yang selama dua minggu menggantung di langit Agam akhirnya runtuh bersama tanah, batang pohon, dan serpihan hutan.
Sekitar pukul 17.30 WIB, suara asing muncul dari hulu. Bagi sebagian warga, bunyinya mirip baling-baling helikopter yang mendekat. Bagi yang lain, justru terdengar seperti dentuman bom yang datang bergulung.
Tak ada yang menyangka bahwa suara itu adalah tanda sebuah galodo paling besar dalam ingatan hidup mereka.
Sungai kecil selebar 10 meter yang selama puluhan tahun menjadi sumber air tiba-tiba meledak menjadi arus selebar separuh kilometer.
Ia menghantam perkampungan seperti binatang raksasa yang lepas dari kandang, liar, cepat, dan tak memberi ampun.
Hanya dalam hitungan menit, tiga kampung tersapu sampai ke fondasinya, Kampung Pilih, Kampung Jambak, dan Sawah Laweh.
Zul, salah satu warga, berdiri mematung di antara batang-batang pohon kelapa yang tumbang.
"Orang-orang tua pernah cerita tentang galodo besar, tapi tidak ada yang sebesar ini. Dua kampung hilang. Habis," ucapnya, masih sulit percaya.
Bagi Izul, kenangan paling membekas adalah suara.
"Suaranya yang saya ingat. Seperti helikopter, keras sekali. Sekali dengar, langsung datang air itu. Tidak sempat apa-apa," kenangnya.
Ia menunjuk bekas rumah tetangganya, kini hanya ruang kosong yang dipenuhi lumpur coklat. Yang tersisa hanyalah atap seng yang tersangkut di batang pohon puluhan meter jauhnya.
Bagi Ilham, luka itu lebih pribadi. Rumah dan bengkelnya hilang, termasuk sepeda motor pelanggan yang ia rawat untuk makan sehari-hari.
Yang tak pernah bisa ia lupakan adalah momen ketika istrinya berteriak menyebut nama-nama anggota keluarga sambil berlari dari terjangan lumpur.
"Kami selamat. Tapi ada bibi di keluarga istri yang tidak sempat. Habis semua. Sekejap saja," katanya, matanya menerawang.
Empat hari setelah bencana, Agam berubah menjadi kota sunyi yang penuh sirene. Setiap beberapa jam, ambulans menuju RSUD Lubuk Basung membawa temuan baru, kadang satu jenazah, kadang dua, kadang satu keluarga sekaligus.
Hingga Selasa (2/12/2025), 102 jenazah sudah dievakuasi. 97 di antaranya berhasil diidentifikasi, sementara lima lainnya masih menunggu nama dan sejarah hidupnya dikembalikan.
Di posko pengungsian, pagar sekolah berubah menjadi tempat menjemur pakaian yang diselamatkan seadanya.
Di sudut tenda, selalu ada satu atau dua orang yang duduk diam, entah menunggu kabar korban yang belum ditemukan, atau masih terjebak antara syukur dan kehilangan.
Bantuan berdatangan seperti denyut baru bagi desa yang hancur. BNPB, TNI, Polri, dan berbagai relawan memasuki kawasan bencana.
Dari Riau, 290 personel kepolisian diperbantukan. Mereka bekerja dalam tiga ritme, mengangkat korban, membuka jalan, dan mengembalikan kehidupan.
Setiap hari, dua dapur lapangan beroperasi. Mereka memasak 3.000 porsi makanan untuk para pengungsi, angka yang menunjukkan betapa banyaknya kehidupan yang terpisah dari rumahnya.
"Fokus kami ada tiga, evakuasi, logistik, dan keamanan," kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto.
Di balik kalimat resmi itu, terlihat kelelahan yang sama yang tampak di wajah para relawan lain. Lumpur setinggi lutut dan medan yang terputus membuat kerja mereka seperti repetisi tanpa akhir.
Namun bahkan setelah bantuan tiba, ancaman baru muncul, krisis air bersih.
Pipa air yang mengalir dari hulu hilang ditelan lumpur. Sungai yang dulu jernih kini berwarna coklat gelap, bau tanah, batang kayu, dan puing.
Polda Riau memasang alat penyuling air di Posko SMPN 3 Palembayan. Setiap tetesnya menjadi harapan kecil bagi ratusan warga yang setiap hari mengantre.
Di Agam, galodo bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peristiwa yang merenggut cerita, suara, masa depan, dan arah hidup.
Di tengah hamparan lumpur itu, orang-orang mencari apa pun yang tersisa, foto keluarga yang basah, piring yang pecah, atau sekadar alasan untuk bangkit.
Dan ketika matahari sore menyinari reruntuhan kampung yang hilang, satu hal menjadi jelas, mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga lembar sejarah yang tak akan pernah sama lagi.