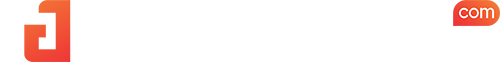PEKANBARU (RA) - Rencana pemerintah menaikkan kadar campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 memicu respons kritis dari pelaku industri sawit nasional. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menilai bahwa persoalan terbesar bukan pada ketersediaan bahan baku, melainkan pada kesiapan teknologi dan aspek ekonominya.
Sahat menegaskan bahwa pasokan crude palm oil (CPO) Indonesia secara teoritis mampu memenuhi kebutuhan tambahan sekitar 3,2 juta ton per tahun. Namun, penerapan B50 harus didekati dengan sangat hati-hati.
"Dalam hal persediaan, saya kira tidak masalah. Tapi karakteristik FAME (fatty acid methyl ester) sebagai biodiesel berbeda dengan solar fosil biasa. Ini perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati," ujar Sahat, Kamis (4/12/2025).
Menurut Sahat, sifat FAME yang mengandung oksigen dan memiliki gugus karboksil membuatnya mudah menyerap air. Kondisi ini dapat memicu penurunan kualitas bahan bakar dan kerusakan mesin diesel dalam jangka panjang, terutama pada unit mesin yang belum diuji kompatibilitasnya dengan B50.
"Kalau B50 dipaksakan tanpa uji teknis menyeluruh, bisa menimbulkan kerusakan mesin dan justru meningkatkan total biaya nasional. Jangan sampai tujuan penghematan energi malah berbalik merugikan," tegasnya.
Saat ini Indonesia masih mengandalkan teknologi esterifikasi untuk memproduksi FAME. Sahat menilai teknologi tersebut sudah ketinggalan dan tidak efisien untuk target jangka panjang menuju B100.
"FAME itu oksigenat, serap air. Kalau disimpan lama, kualitasnya turun. Teknologi alternatif seperti hydrogenated vegetable oil (HVO) atau HVU sebenarnya sudah dijajaki sejak tiga tahun lalu, tapi kenapa belum dijalankan?" katanya.
HVO dinilai lebih unggul karena menghasilkan bahan bakar drop-in yang kualitasnya setara solar fosil dan dapat digunakan tanpa modifikasi mesin.
Sahat juga menyoroti aspek ekonomi. Dengan harga minyak dunia turun di bawah USD 60 per barel, biaya produksi biodiesel berbasis CPO menjadi tidak kompetitif. Harga CPO sekitar USD 950 per ton, ditambah biaya produksi USD 85, membuat harga biodiesel FAME mencapai sekitar USD 138 per barel.
Angka tersebut jauh di atas harga solar Euro 5 impor yang hanya sekitar USD 86 per barel.
"Selisihnya bisa sampai USD 50 per barel. Kalau dikalikan 3 juta ton, itu kerugian sekitar USD 240 juta. Siapa yang menanggung? Ini perlu dipikirkan secara matang," ujar Sahat.
Ia menambahkan, nilai tambah FAME dari CPO hanya sekitar USD 85, sedangkan produk bio lain dapat menghasilkan nilai hingga USD 2.800 per ton. Menurutnya, strategi hilirisasi perlu diperluas, tidak hanya terpaku pada biodiesel.
"Kenapa kita tidak kembangkan produk bio lain yang lebih bernilai? Jangan hanya ikut euforia. Perlu roadmap yang jelas, riset yang matang, dan keputusan berbasis fakta," katanya.
Menanggapi arahan Presiden dan Menteri ESDM soal kemandirian energi, Sahat menyatakan dukungannya. Namun, ia menegaskan bahwa tujuan besar tersebut membutuhkan strategi yang tepat, bukan sekadar percepatan simbolik.
"Kalau kita berharap FAME bisa sampai B100, itu melawan hukum alam. Kita butuh terobosan teknologi dan strategi yang realistis," ujarnya.
Di tengah penurunan produktivitas sawit nasional, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan suplai bahan baku agar kebijakan energi tidak menimbulkan masalah baru.
"Jangan sampai karena terlalu terburu-buru, kita justru menciptakan masalah baru. Ini saatnya berpikir strategis, bukan sekadar simbolik," tutup Sahat.